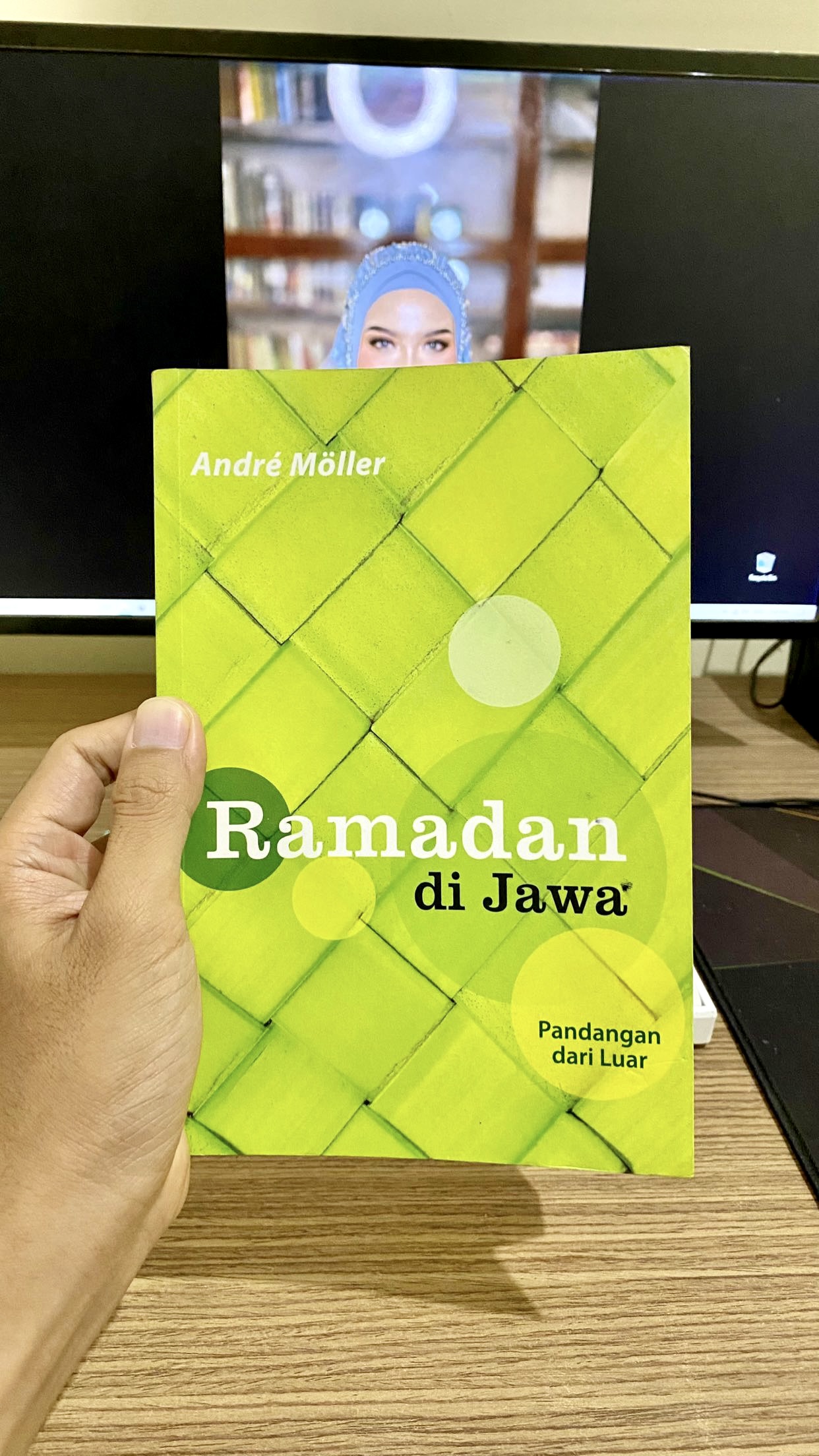After the Prophet: Menelusuri Asal-usul Perpecahan Sunni dan Syi’ah
Baik sejarawan Sunni seperti Ahmad Amin maupun sejarawan Syi’ah seperti Muhammad Husain Thabathaba’i sepakat bahwasanya perpecahan antara Sunni dan Syi’ah bermula setelah Nabi wafat. Saat itu terjadi perdebatan di kalangan umat Islam terkait siapa yang paling berhak melanjutkan kepemimpinan Nabi. Kelompok Sunni menginginkan kepemimpinan umat Islam ditentukan secara musyawarah sedangkan kelompok Syi’ah menginginkan Ali bin Abi Thalib ditunjuk langsung sebagai pengganti Nabi.
Namun, jika ditelusuri lebih jauh, pada dasarnya bibit-bibit perpecahan itu sudah ada semenjak Nabi hidup. Lesley Hazleton dalam After the Prophet: The Epic Story of the Shia-Sunni Split in Islam berusaha menelusuri muasal keretakan tersebut. Peneliti yang banyak merujuk karya Ibnu Jarir al-Thabari dalam bukunya ini kemudian menemukan bahwasanya keretakan tersebut terjadi akibat adanya perselisihan antara ‘Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib.
Dibandingkan dengan istri-istri Nabi yang lain, ‘Aisyah memang memiliki kecemburuan khusus terhadap Khadijah—istri pertama Nabi sekaligus ibu mertua Ali bin Abi Thalib. Secara mengejutkan ‘Aisyah pernah bertanya kepada Nabi mengapa beliau masih tetap saja setia mengenang “wanita tua ompong yang Allah telah ganti dengan yang lebih baik” itu.
Menyikapi hal ini, Nabi menegur ‘Aisyah dengan tegas. Beliau menjawab bahwa Allah tidak pernah menggantikan sosok Khadijah dengan perempuan yang lebih baik. Allah justru telah menganugerahi Nabi dengan anak-anak yang lahir dari Khadijah, bukan dari istri-istrinya yang lain.
Pembelaan Nabi atas Khadijah bukannya tanpa alasan. Beliau menikah dengannya pada usia 25 tahun. Selama menikah dengan Khadijah, Nabi menjalani kehidupan rumah tangganya secara monogami. Khadijah adalah orang pertama yang beriman ketika Nabi diangkat menjadi utusan. Beliau juga merupakan orang yang mendermakan seluruh hartanya demi kepentingan dakwah Nabi. Dengan demikian, Khadijah menempati tempat khusus di hati Nabi.
Karena ‘Aisyah tidak bisa mengungkapkan kekesalannya kepada Khadijah (sebab beliau sudah meninggal), ia pun melampiaskannya kepada Fatimah, putri sulung Khadijah yang juga istri dari Ali bin Abi Thalib.
Dalam After the Prophet, Lesley Hazleton menulis bahwa ‘Aisyah memiliki semacam pengaruh dan dengan satu atau lain cara dia menggunakannya untuk menyindir dan menghina Fatimah secara samar maupun terang-terangan. Kejadian seperti ini terus berulang hingga akhirnya para istri Nabi yang lain meminta Fatimah untuk menemui ayahnya dan memprotes laku pilih kasih Nabi terhadap ‘Aisyah.
Perselisihan antara ‘Aisyah dan Ali bin Abi Thalib semakin parah ketika ‘Aisyah dituduh telah melakukan perbuatan serong oleh rombongan orang-orang munafik. Dalam peristiwa yang dikenal dengan sebutan “Kasus Kalung” itu Nabi meminta pendapat Ali bin Abi Thalib lantaran beliau tidak memperoleh petunjuk selama beberapa waktu.
Ali bin Abi Thalib kemudian menganjurkan Nabi agar menceraikan ‘Aisyah. Menurutnya, itu adalah jalan terbaik untuk meredam berbagai macam gunjingan yang beredar di tengah-tengah umat Islam. “Banyak wanita seperti dia. Allah telah membebaskanmu dari masalah ini. Gampang mencari penggantinya. Ceraikan ‘Aisyah dan selesai sudah kasus itu,” jawab Ali bin Abi Thalib.
Walaupun pada akhirnya turun ayat yang menyatakan bahwa ‘Aisyah tidak melakukan perselingkuhan, namun ‘Aisyah terlanjur menyimpan dendam kepada Ali bin Abi Thalib. Lesley Hazleton kemudian menganggap ucapan Ali bin Abi Thalib ini sebagai pernyataan terbuka pertama yang meretakkan batu pondasi Islam yang baru saja tertanam. Retakan tersebut halus. Pada awalnya hampir tak terlihat, tapi terus melebar dan berubah menjadi patahan besar.
“Lontaran kata-kata Ali yang merendahkan, penghinaan yang bisa dikatakan terbuka, tidak hanya menyengat tubuh tapi juga menusuk sampai ke tulang. Justru kesengajaan inilah yang membuat pernyataan tersebut menjadi begitu meyakinkan. Kata-kata merendahkan yang diucapkan Ali, penghinaan yang terang-terangan, keyakinan yang jelas untuk mempercayai perselingkuhan ‘Aisyah—semua inilah yang ‘Aisyah terus lawan selama sisa hidupnya,” tulis Lesley Hazleton.
Tampaknya, latar belakang Lesley Hazleton sebagai seorang psikolog berhasil memberikan sudut pandang alternatif atas konflik yang terjadi antara Sunni dan Syi’ah. Selama ini para sejarawan menganggap konflik tersebut sebagai konflik politik (karena berkaitan dengan siapa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Nabi) yang kemudian bertransformasi menjadi konflik teologis (karena pihak-pihak terkait menjadikan agama sebagai pembenarannya).
Namun, bagi Lesley Hazleton, itu semua berawal dari masalah pribadi anggota keluarga Nabi. Tanpa disadari, rivalitas ‘Aisyah dan Ali bin Abi Thalib selama bertahun-tahun telah menjadi salah satu penyebab konflik sektarian terbesar di dalam Islam yang menelan banyak korban jiwa—termasuk cucu Nabi sendiri.
Berlawanan dengan doktrin Sunni yang menyatakan bahwa “setiap sahabat adalah adil”, dalam buku ini Lesley Hazleton justru ingin menunjukkan sisi-sisi manusiawi mereka. Karena bagaimanapun juga para sahabat Nabi adalah manusia biasa yang juga melakukan kesalahan.
Ditulis dengan gaya bertutur layaknya novel, buku ini jauh dari kata kaku dan membosankan. Dengan membaca bagian-bagian yang ada di dalamnya, Anda akan dibuat seolah-olah sedang duduk di tengah padang pasir lalu mendengarkan seorang pendongeng menuturkan ceritanya.
Lesley Hazleton membagi bukunya dalam tiga bagian. Bab pertama berjudul “MUHAMMAD” yang menceritakan hari-hari terakhir sebelum beliau wafat serta konflik yang terjadi antara ‘Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Bab kedua berjudul “ALI” yang menceritakan posisi politik Ali bin Abi Thalib pasca wafatnya Nabi serta pecahnya Perang Jamal. Sedangkan bab terakhir, yang berjudul “HUSSEIN”, menceritakan tragedi Karbala di mana cucu Nabi beserta 72 orang lainnya dibantai oleh pasukan Yazid bin Muawiyah.
Sebagian besar sumber rujukan buku ini berasal dari Tarikh al-Rusul wa al-Muluk karya al-Thabari. Ada alasan khusus mengapa Lesley Hazleton merujuk tulisan al-Thabari. Menurutnya, al-Thabari adalah sejarawan Sunni yang pengetahuan sejarahnya luas sehingga sama-sama diakui oleh golongan Sunni maupun golongan Syi’ah.
Katanya, dia memanfaatkan sejarah lisan secara menyeluruh, bepergian mengunjungi wilayah-wilayah Islam untuk melakukan wawancara dan mendokumentasikannya dengan rinci supaya rantai sanadnya menjadi jelas. Perhatian al-Thabari terhadap hal-hal kecil juga menjadi bahan pertimbangan Lesley Hazleton.
“Tarikh, dengan demikian, memiliki kualitas keotentikan yang orang Barat cenderung tidak temukan dalam sejarah-sejarah klasik. Suara-suara dari abad ketujuh ini—tidak hanya bagi orang-orang yang dia wawancarai namun juga bagi orang-orang yang mereka bicarakan, yang sering mereka kutip kata demi kata—tampak seakan langsung bicara kepada pembaca. Hasilnya begitu jelas. Bahkan Anda hampir bisa mendeteksi perubahan nada suara mereka dan melihat gerak tubuh mereka saat sedang bicara. Jika dibandingkan dengan karya sejarawan Islam awal yang lainnya, agaknya karya ini memiliki kualitas yang lebih unggul,” tulis Lesley Hazleton.
Penulis: Lesley Hazleton
Penerbit: IRCiSoD
Oleh: Inan
*Tulisan ini pertama kali diterbitkan di arina.id