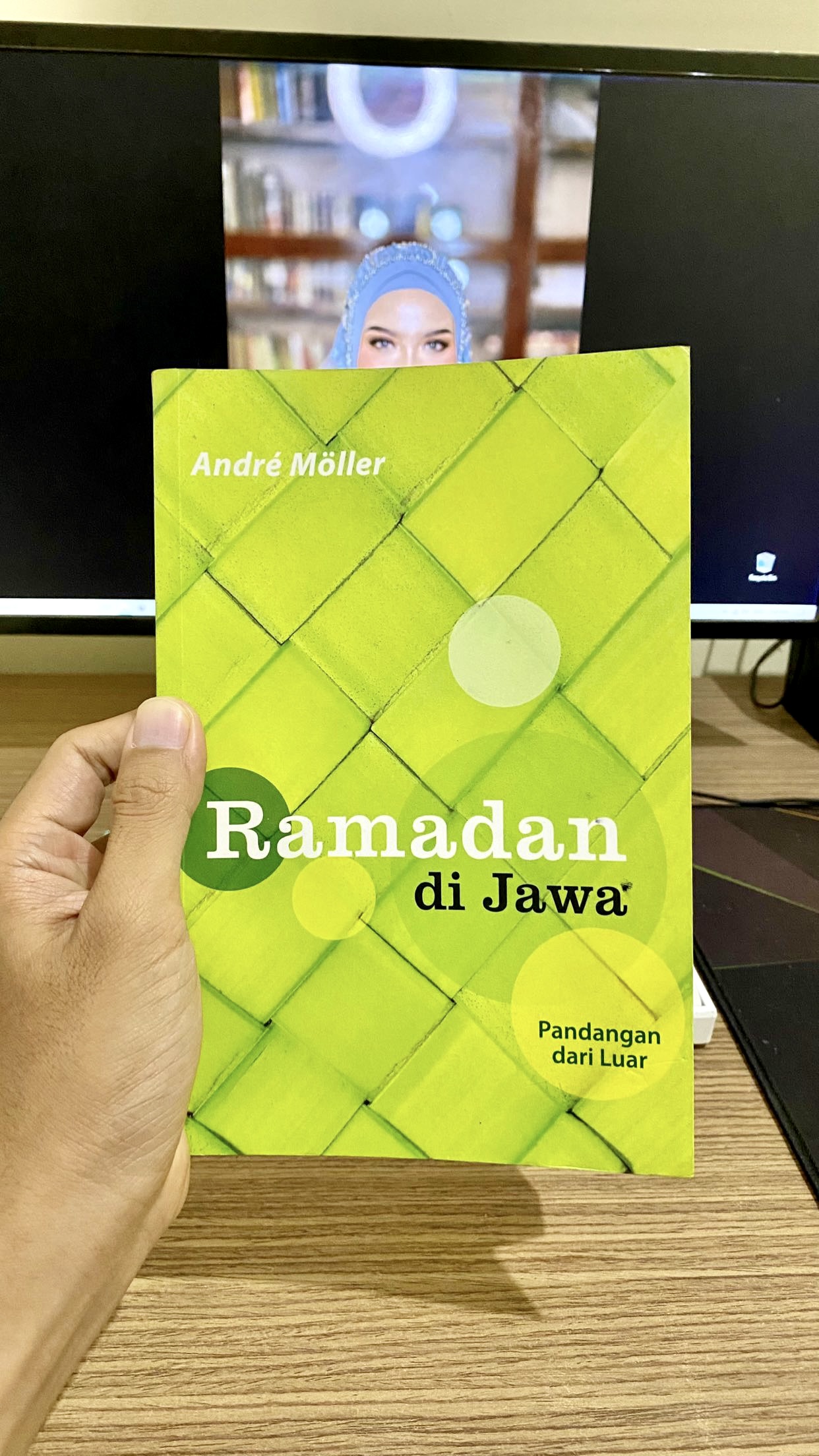Rumah Kaca: Upaya Pemerintah Kolonial Melumpuhkan Gerakan Pribumi Melalui Politik Arsip
Serial Tetralogi Buru ditutup dengan novel terakhirnya yang berjudul Rumah Kaca. Walau masih berbicara tentang tumbuhnya benih-benih nasionalisme di Indonesia, novel ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan ketiga novel pendahulunya.
Perbedaan itu salah satunya ialah hilangnya suara Minke. Dalam Rumah Kaca, Minke tak lagi menjadi orang pertama yang berkisah tetapi menjadi orang ketiga yang dikisahkan melalui sudut pandang Jacques Pangemanann.
Jika dalam Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, dan Jejak Langkah kita melihat keadaan sosial Hindia Belanda dari mata kepala seorang pribumi, maka dalam Rumah Kaca kita melihatnya melalui mata kepala seorang peranakan Eropa yang menjadi kaki-tangan pemerintah kolonial.
Menurut saya, perpindahan narator dari Minke menuju Pangemanann ini merupakan bentuk kepiawaian Pramoedya dalam bercerita. Sebagai penulis dia berhasil memanfaatkan perbedaan latar belakang tokoh-tokohnya untuk membangun cita rasa bahasa yang berbeda-beda.
Konsekuensinya, Tetralogi Buru menjadi novel dengan nuansa bahasa yang beragam. Dalam Rumah Kaca misalnya, kita akan menemukan gaya bertutur Pangemanann yang betul-betul berlainan dengan Minke—komplit dengan istilah-istilah khasnya seperti umpatan “zihhh” dan “cihhh”.
Rumah Kaca dibuka dengan monolog Pangemanann yang menceritakan keputusasaan Gubernur Jenderal Idenburg dalam membendung bangkitnya nasionalisme Asia di Hindia Belanda.
Pada tahun 1911, seorang dokter bernama Sun Yat Sen berhasil memimpin revolusi di Tiongkok dan menjadi presiden pertama di sana. Semua mata dunia tertuju padanya. Mereka menunggu tindakan apa yang hendak diambil oleh presiden tersebut.
Kabar tentang kesuksesan Revolusi Tiongkok segera tersebar di wilayah-wilayah jajahan Eropa di Asia—tak terkecuali Hindia Belanda. Walhasil, banyak penduduk wilayah jajahan yang terinspirasi untuk melakukan hal serupa.
Dengan semangat nasionalisme, orang-orang peranakan Tiongkok di Betawi menerbitkan koran Sin Po. Di Bandung, seorang pengagum Revolusi Tiongkok, seorang raden, sekaligus siswa STOVIA yang gemar mengajak golongan lemah untuk melawan golongan kuat dengan senjata bernama “boikot” menerbitkan koran pertama berbahasa Melayu dengan nama Medan Prijaji.
Kebangkitan nasionalisme ini, meskipun tidak melanggar suatu hukum tertentu yang berlaku di Hindia Belanda, tetap harus dijinakkan. Alasannya: setiap kegiatan yang mengarah kepada pemusatan kekuatan akan selalu menjadi ancaman bagi pemerintah kolonial. Kalaupun tidak menimbulkan ancaman, kegiatan itu dapat mengurangi kewibawaan mereka.
Lalu, siapakah orang yang ditunjuk Gubermen untuk melumpuhkan ancaman tersebut? Jawabannya adalah: Pangemanann dengan “n” ganda. Berbeda dengan tugas polisi Hindia Belanda pada umumnya, Pangemanann mendapatkan mandat khusus yakni: memata-matai setiap gerak-gerik pribumi.
Pangemanann mengistilahkan kegiatan memata-matainya sebagai strategi “Rumah Kaca”. Setiap orang yang dia curigai akan dimasukkan ke dalam daftar pengawasannya. Dari situ, Pangemanann kemudian melacak segala informasi terkait orang-orang tersebut mulai dari tempat tinggal, relasi keluarga, aktivitas dan pergerakannya, sampai tulisan-tulisan mereka yang terbit di koran.
Berdasarkan berkas-berkas yang tersebar di lembaga pengarsipan dan kantor pemerintah setempat, Pangemanann lantas meneliti, menganalisa, membandingkan, lalu membuat rekomendasi apakah mereka berbahaya bagi pemerintah kolonial atau tidak. Dan bagi mereka yang dianggap berbahaya, pengasingan adalah ganjarannya.
“Bukankah sudah jelas? Baik sebagai Inspektur maupun Komisaris Polisi, pekerjaanku tak lain terus mengawasi ketat sebangsaku demi keselamatan dan kelangsungan hidup Gubermen. Semua pribumi—terutama Pitung-Pitung modern yang mengusik-usik kenyamanan Gubermen—semua telah dan akan kutempatkan dalam sebuah rumah kaca dan kuletakkan di meja kerjaku. Segalanya menjadi jelas terlihat. Itulah pekerjaanku: mengawasi semua gerak-gerik seisi rumah kaca itu.” Demikian kata Pangemanann.
Perkara seperti ini memang lazim dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap tanah jajahannya. Beberapa tahun sebelumnya, ketika Belanda kewalahan menaklukkan Aceh, mereka mengirim Snouck Hurgronje untuk melakukan penelitian di sana.
Penelitian tersebut bertujuan untuk mengungkap faktor apa saja yang menyebabkan bangsa Aceh begitu sulit ditaklukkan bahkan sampai bertahun-tahun. Snouck Hurgronje kemudian menemukan bahwa salah satu penyebabnya adalah ajaran Islam.
Menurutnya, Islam sebagai agama tidak hanya berkaitan dengan persoalan ibadah seperti sholat, zakat, puasa ataupun haji. Lebih dari itu, Islam juga merupakan doktrin politik. Islam mengajarkan umatnya untuk mengangkat senjata terhadap setiap ketidakadilan dan kezaliman. Ajaran-ajaran itulah yang kemudian menjadi bahan bakar utama bangsa Aceh dalam perang melawan penjajah.
Snouck lantas merekomendasikan pemerintah kolonial untuk menindak tegas jenis Islam yang kedua ini. Hasilnya, tiap kegiatan agama yang berkaitan dengan ibadah tidak dilarang. Namun, jika berkaitan dengan politik, pemerintah akan segera mengambil tindakan.
Setiap ulama diawasi gerak-geriknya. Mereka didata dan ditandai. Orang-orang yang pulang dari tanah suci pun diberi label “haji”. Para ulama tetap diperbolehkan untuk berbicara di atas mimbar dengan syarat tidak menyerukan perlawanan. Sekali saja mereka berbicara tentang hal tersebut, maka pada saat itu pula mereka ditangkap dan diasingkan.
Dalam upayanya melumpuhkan gerakan pribumi di Hindia Belanda, Pangemanann bukannya tidak mengalami dilema. Jauh di dalam lubuk hatinya dia menyadari bahwa tindakannya itu bertentangan dengan kemanusiaan.
Pada sebuah surat yang ditujukan untuk keluarganya, Pangemanann membuat pengakuan bahwa selama ini dia telah berbohong kepada mereka. Dia tidak sebaik penilaian keluarganya. Dengan nada putus asa Pangemanann berpesan agar anak-anaknya tidak mengambil jalan yang sama dengan dirinya.
Nuraninya memberontak ketika melihat kesewenang-wenangan pemerintah kolonial terhadap penduduk jajahannya. Namun, karena mengejar jabatan dan posisi terpandang, Pangemanann mengorbankan prinsipnya dan menjadi jongos Eropa.
“Untuk keselamatan diri hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh: bermuka dua dan berhati banyak dengan sadar. Setelah terlatih membiasakan diri bermuka dan berhati belah berkeping-keping begini, maka nurani ini sudah cukup kuat untuk melahirkan watak baru bagi manusia Pangemanann ini. Namun aku selalu saja merindukan manusia Pangemanann yang dulu, yang tulus, yang sederhana, yang percaya pada kebajikan manusia. Dan hanya aku sendiri yang paling tahu, bagaimana dalam kehidupan batin pemisahan dan pembelahan ini kadang-kadang tak dapat dipertahankan, serang-menyerang, kalah-mengalahkan, ejek-mengejek, bergalau jadi medan-perang riuh. Dua-duanya harus menang. Harus! Yang satu bernama prinsip, yang lain bernama penghidupan.”
Sebagai antagonis utama dalam Rumah Kaca, Pangemanann merupakan pribadi yang mengagumi musuh-musuhnya. Berkali-kali dia mengungkapkan kekagumannya terhadap pendiri Sarekat Dagang Islam itu.
Bagi Pangemanann, apa yang dikerjakan oleh Minke pada dasarnya bukanlah suatu tindakan kriminal. Dia bukan seorang penjahat maupun pemberontak. Dia hanya seorang pribumi terpelajar yang terlalu mencintai bangsanya. Baginya, Minke hanya mencoba memajukan bangsanya dan berusaha menegakkan keadilan di bumi Hindia Belanda.
“Manusia dengan banyak kelebihan ini, aku secara pribadi benar-benar menghormatinya dengan tulus. Ia telah mencapai jauh—jauh—jauh lebih banyak daripada yang dapat kugapai dalam hidupku yang lebih tua. Aku hormati dia dengan diam-diam.” Tutur Pangemanann pada suatu kali.
Sampai di sini, lagi-lagi kita bisa melihat kepiawaian Pramoedya dalam menulis. Ketika menggambarkan tokoh antagonisnya dia tidak hanya memperlihatkan perilaku jahat tokohnya begitu saja. Tapi, Pramoedya juga mengungkapkan latar belakangnya, motif-motif tindakannya, bagaimana konflik batin yang dialami oleh mereka sampai akhirnya mereka berubah menjadi sosok antagonis. Secara tidak langsung Pramoedya mengajarkan kita untuk tidak memandang persoalan secara hitam-putih.
Dan sebagaimana dalam buku-bukunya yang lain, kita juga bisa menemukan kritik Pramoedya terhadap watak bangsa Jawa dalam bukunya ini. Bagi saya, ada satu kritik pedas Pramoedya terhadap bangsa Jawa yang masih relevan sampai sekarang yaitu: kebiasaan mereka larut dalam prinsip orang lain demi menghindari konflik.
Menurut Pramoedya, bangsa Jawa adalah bangsa yang mudah ditaklukkan karena mereka memiliki watak untuk selalu mencari kesamaan, keselarasan, dan melupakan perbedaan agar terhindar dari benturan sosial. Mereka selalu tunduk pada prinsip ini hingga terkadang tidak menyadari batasan-batasannya. Akibatnya, mereka cenderung jatuh dari satu kompromi menuju kompromi yang lain dan kehilangan prinsip.
Sebagai pembaca yang lahir, hidup, dan tinggal di Jawa, saya tidak bisa jika tidak mengamini pernyataan ini.
Judul: Rumah Kaca
Penulis: Pramoedya Ananta Toer
Penerbit: Lentera Dipantara
Jumlah halaman: 646 halaman
Oleh: Inan
(Dukung kami untuk terus menyajikan tulisan berkualitas dengan berdonasi di sini.)