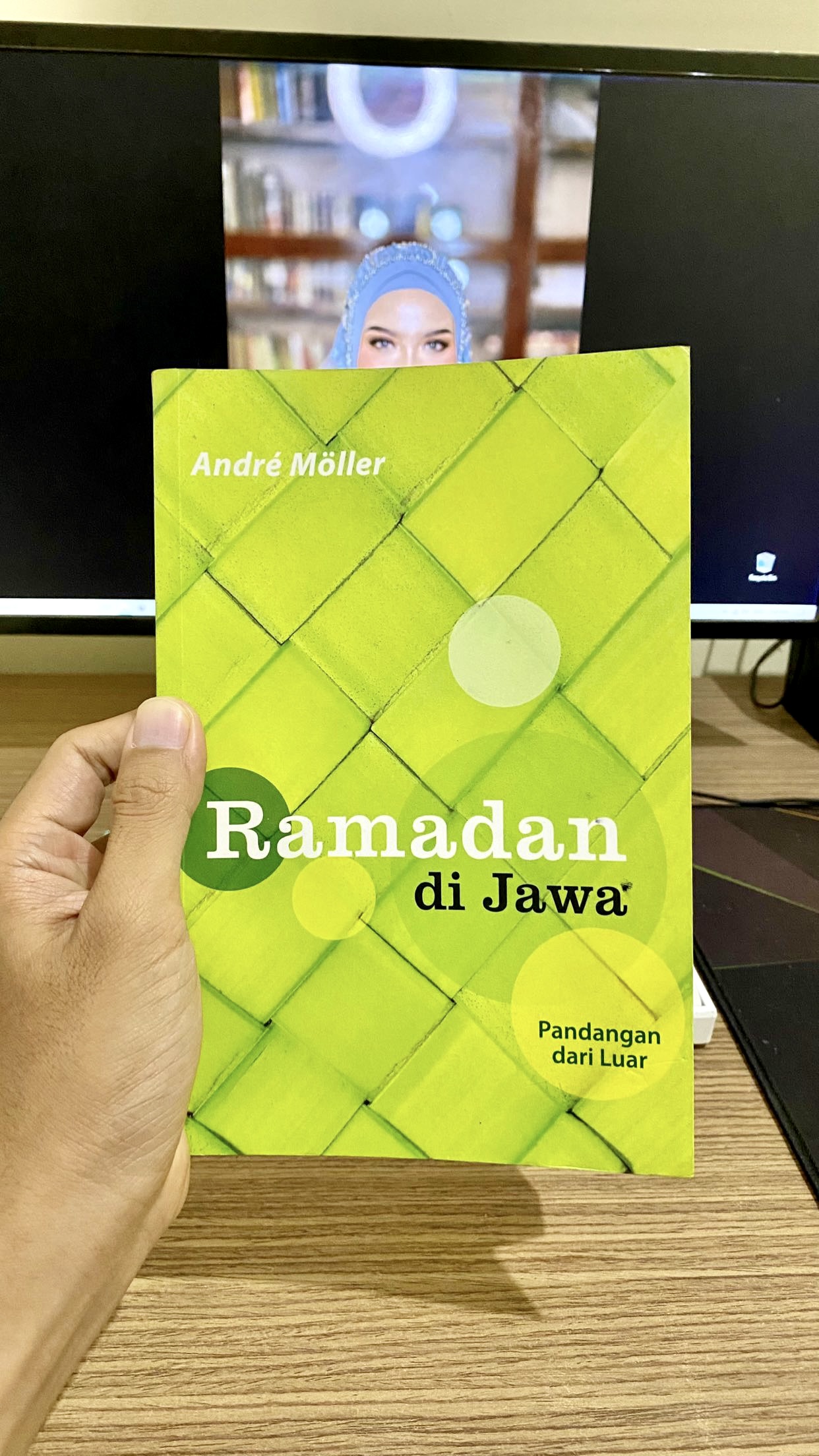Memoar Muram dari Kamp Pengasingan
Ada dua buku yang selesai saya baca terkait nasib para tahanan politik Orde Baru di Pulau Buru. Buku pertama berjudul Bertahan Hidup di Pulau Buru karya Mars Noersmono dan buku kedua berjudul Nyanyi Sunyi Seorang Bisu milik Pram.
Kedua buku itu ditulis oleh penulisnya ketika mereka diasingkan di Pulau Buru. Mars Noersmono diasingkan di sana selama delapan tahun sementara Pramoedya A. Toer selama sepuluh tahun.
Keduanya sama-sama berisi memoar yang muram. Bedanya, selain terdiri dari catatan pribadi penulisnya, Nyanyi Sunyi Seorang Bisu juga terdiri dari surat-surat Pram untuk keluarganya.
Nyanyi Sunyi Seorang Bisu terbagi menjadi dua jilid. Jilid pertama berisi catatan Pram selama di Pulau Buru sedangkan jilid kedua berisi riwayat kehidupan masa kecilnya sampai sebelum dia berada di pengasingan.
Jilid pertama Nyanyi Sunyi Seorang Bisu dibuka dengan surat berjudul Perapungan dan Permenungan. Surat itu ditulis oleh Pram untuk putrinya yang baru saja menikah.
Tanpa mengetahui apakah suratnya sampai ke tujuan atau tidak, dia menuliskan permintaan maafnya karena hadiah pernikahan untuk putrinya justru berwujud pembuangan sang ayah di pulau terpencil.
Di dalam surat itu Pram menceritakan hari-hari keberangkatannya menuju kamp pengasingan. Dia diangkut menuju Pulau Buru dengan kapal yang sangat jauh dari kata bersih. Lantainya dikuasai kecoa. Kakusnya penuh dengan kotoran manusia. Saking banyaknya, kotoran manusia itu sampai menyerupai genangan lumpur.
Meskipun sudah udzur, kapal tersebut tetap beroperasi. Beberapa kali ia mogok. Terombang-ambing di tengah lautan. Sebagian penumpangnya putus asa. Ada yang berdoa dan berharap kapal tersebut tenggelam dihantam angin timur dan semua penumpangnya mati dimakan ikan hiu. Namun, nasib berkata lain. Ternyata kapal tersebut selamat sampai tujuan.
Di Pulau Buru Pram mendekam tanpa proses pengadilan. Pada salah satu wawancaranya dengan tim psikologi gabungan antara UI dan UGM yang saat itu mengunjungi Pulau Buru, dia mengatakan:
"Saya merasa diperlakukan tidak menurut hukum. Belum pernah saya dijatuhi hukuman oleh sesuatu pengadilan. Saya adalah seorang pengarang. Saya menulis dengan nama jelas. Sekiranya ada kesalahan atau kekeliruan dalam tulisan saya, setiap orang boleh dan berhak menyalahkan, apalagi pemerintah yang notabene mempunyai kementrian penerangan. Maka, mengapa saya ada di sini? Sekiranya saya bersalah, saya akan rela menerima hukuman."
Perpustakaan yang telah dibangunnya selama 20 tahun pun dihancurkan begitu saja oleh aparat. Pada waktu penangkapannya dia mempersilahkan koleksi perpustakaannya untuk diambil asal diselamatkan karena dapat berguna untuk kepentingan nasional. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.
Di pulau yang luasnya 13 kali lebih besar daripada Singapura, Pram bersama ribuan tahanan lainnya dipaksa untuk membuka jalan tanpa peralatan karena memang belum ada. Mereka mencabuti alang-alang setinggi 2 meter lebih dan rumput-rumput tajam dengan tangan kosong. Peralatan baru datang 10 hari kemudian.
Jatah makan mereka berkurang dari hari ke hari. Awal mulanya 600 gram beras. Lalu, menyusut menjadi 500 gram. Perlahan-lahan semuanya hilang satu per satu hingga pada suatu apel pagi, Pram melihat salah satu kawannya menjatuhkan diri dalam barisan karena melihat seekor kadal. Dia menangkapnya untuk kemudian dimakan dengan harapan memperoleh protein hewani dari reptil berkaki empat itu.
Begitu pula dengan Pram. Dia bertahan hidup dengan cara memakan tikus, serangga, dan ular.
Lebih lanjut, buku ini juga merekam latar belakang penulisan beberapa novelnya dan juga menceritakan bagaimana Pram memperoleh inspirasi untuk para tokoh yang ada di dalamnya. Pada novel Arus Balik misalkan, ide penulisannya muncul ketika dia memikirkan Periode Kebangkitan Nasional dalam sejarah bangsa Indonesia.
“Aku telah berjanji untuk menulis roman lagi pada umurku yang empat puluh tahun. Tepat pada umur tersebut aku justru masuk dalam tahanan, 1965, dan semua yang telah aku kumpulkan dengan susah-payah dan mahal binasa di tangan orang-orang yang tidak mengerti…”
“Jadi aku tunda menulis novel sambil melatih diri untuk mengingat dan menggapai-gapai dalam kegelapan. Sementara itu timbul satu problem, kalau ada Periode Kebangkitan Nasional, tentu ada periode kejatuhannya, kejatuhan yang mendahului. Dengan demikian mulai aku siapkan menulis tentang kejatuhannya dahulu, yakni masa tengah pertama abad keenam belas. Dan akupun mulai menulis Arus Balik,” demikian tuturnya.
Sedangkan pada novel Bukan Pasar Malam, yang menceritakan kekecewaan seorang nasionalis terhadap rekan-rekan seperjuangannya karena mereka sibuk memperkaya diri sendiri, didasarkan pada kisah perjalanan hidup ayahnya.
Pram menggambarkan sosok ayahnya sebagai orang yang tidak pernah melanggar hak seseorang atau mengurangi pribadinya. Ia pun mengaguminya. Kalaupun punya cacat, itu adalah kesukaannya bermain judi.
Pada bagian yang lain Nyanyi Sunyi Seorang Bisu menceritakan bagaimana penyiksaan terhadap para tapol tidak hanya membuat mereka cacat secara fisik tapi juga secara mental dan bahkan berujung pada bunuh diri.
Di bawah pimpinan seorang kapten bernama Sudjoso Hadisiswojo lima orang kawan Pram meninggal dunia. Menurutnya itu jumlah kematian terbesar. Seorang tapol bernama Samtiar yang saat itu sedang sakit meninggal setelah dipukuli di halaman rumah sakit.
Yang lainnya adalah seorang pemuda asal Malang. Pada suatu kali ia jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Dalam keadaan sakitnya itu dia merasa sangat berhutang dan bersalah kepada teman-temannya karena mereka telah mencukupi kebutuhan dirinya mulai dari makan dan minum, termasuk memasak untuknya.
Dalam keadaan sakit dia dipukuli oleh seorang komandan. Dua hari kemudian dia menyelinap pergi seorang diri ke sebuah gubuk ladang jagung. Di sana dia minum cairan pestisida, mati kesakitan.
Dari sekian banyak laporan kejahatan militer di Pulau Buru, laporan yang paling menyedihkan untuk dibaca adalah laporan Pram mengenai Jiku Kecil. Jiku Kecil merupakan nama sebuah daerah di dalam Pulau Buru. Daerah itu digunakan untuk mengucilkan para tahanan yang dianggap melanggar peraturan. Tidak banyak yang keluar dari sana dalam keadaan hidup.
Berbekal informasi dari kawan-kawannya di unit lain, baik yang berupa catatan maupun lisan, Pram menyusun daftar tahanan politik yang meninggal dunia di Jiku Kecil lengkap beserta nama, daerah asal, pendidikan, penyebab dan tanggal kematiannya. Sebagian dari mereka mati karena bunuh diri dan sebagian yang lain karena dibunuh oleh aparat.
Seorang tahanan asal Surabaya dilaporkan meninggal gantung diri di Barak III Jiku Kecil. Menurut dugaan tahanan lain, dia meninggal lantaran tidak sanggup menjalani pemeriksaan selama seminggu. Setiap hari dia dipaksa untuk memakan tahi kuda dan luka-luka di tubuhnya dioles dengan lombok dan garam.
Lain lagi ceritanya dengan tahanan asal Solo. Dia meninggal pada pukul 10 pagi karena ditembak aparat. Menurut keterangan, dia dibawa ke lapangan yang terletak di depan barak. Sambil berteriak “mau melawan kamu?”, seorang aparat mengacungkan senapan ke arah dirinya. Dalam keadaan menyerah dia ditembak.
Berikutnya, sebuah laporan menyatakan bahwa beberapa orang tapol digiring menuju lapangan sepak bola kemudian dipaksa melakukan gerakan koprol bolak-balik dari satu ujung lapangan menuju ujung yang lain. Sambil koprol mereka dimaki, diancam, dan ditembaki oleh aparat.
Ada pula seorang tapol yang ditembak di bawah bahu—tepatnya pada bagian dada, tidak boleh dirawat, tidak boleh diberi makan dan minum sampai dia meninggal.
Dan dari semua laporan tersebut, tidak ada satu pun pelakunya yang diadili oleh negara. Bahkan, ketika para tahanan yang masih hidup berusaha memberikan penanda pada makam para korban agar suatu saat nanti keluarga almarhum bisa menziarahinya, mereka mendapat ancaman dari aparat. Katanya, mereka akan menindak setiap perbuatan yang menimbulkan kesan “mempahlawankan” para almarhum.
Secara keseluruhan, buku ini mengajak kita untuk menelusuri lorong-lorong sunyi kehidupan penulisnya selama di pengasingan. Sisi-sisi emosional Pram yang jarang kita lihat dalam wawancaranya tampak begitu jelas dalam memoarnya ini. Terutama ketika dia berkorespondensi dengan anak-anaknya.
Selain itu, buku ini juga mengingatkan kita tentang kejahatan kemanusiaan yang pernah dilakukan oleh pemerintah kita di masa lalu. Pada suatu periode, negara yang katanya menjunjung tinggi demokrasi itu pernah melakukan pelanggaran HAM secara besar-besaran.
Tak perlu jauh-jauh pergi menuju kamp Buchenwald, Ravensbrück, Dachau, atau Auschwitz untuk melihat bagaimana perampasan hak asasi manusia di era modern terjadi. Di Pulau Buru kita bisa melihatnya secara terang-terangan dan memoar muram ini merupakan pintu masuk menuju ke sana.
Judul: Nyanyi Sunyi Seorang Bisu
Penulis: Pramoedya Ananta Toer
Penerbit: Hasta Mitra
Jumlah halaman: 750 halaman
Oleh: Inan
(Dukung kami untuk terus menyajikan tulisan berkualitas dengan berdonasi di sini.)