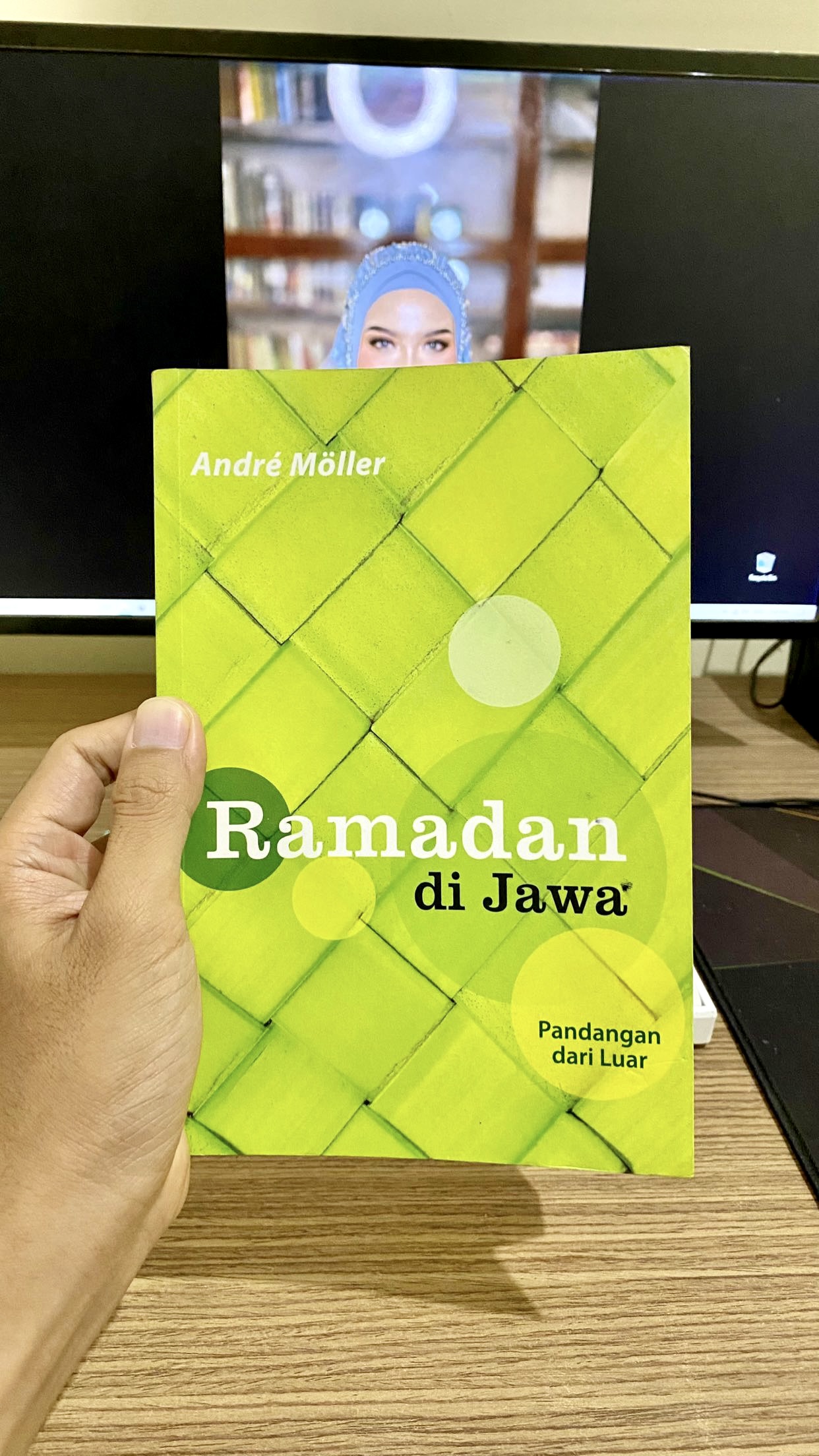Burmese Days, Cara Orwell Menebus Dosa Kolonialnya
Apa yang sebenarnya menarik dari Burmese Days, selain karena bercerita tentang pengalaman hidup Orwell di Burma, ialah karena pembacanya dapat menjadikan novel tersebut sebagai tolok ukur untuk melihat proses perkembangan tulisan Orwell dari waktu ke waktu.
Sebab, Burmese Days adalah novel pertama Orwell. Dan tiap-tiap permulaan, awal, atau “yang pertama” adalah salah satu titik terbaik untuk menimbang sesuatu.
Berbeda dengan novel-novel Orwell yang terbit sesudahnya semisal 1984 atau Animal Farm, Burmese Days cenderung dipenuhi oleh deskripsi panjang lebar serta kiasan-kiasan yang mempesona. Bahasa yang digunakan Orwell pun lebih kompleks tinimbang dalam novel-novel berikutnya.
Agaknya, ketika menulis Burmese Days Orwell masih belum terpikirkan untuk mengikuti enam kaidah menulisnya yang terkenal itu, di mana salah satu poinnya menyebutkan:
“Sebisa mungkin jangan pernah menggunakan kata panjang jika bisa menggunakan kata yang pendek ketika kamu menulis.”
Burmese Days memiliki gambaran detail tentang kondisi geografis wilayah Burma sehingga membuat kisah di dalamnya menjadi lebih hidup. Hutan tropis dengan semak belukar yang tinggi, sungai Irrawaddy yang misterius serta cuaca musim panas khas daerah Asia.
Menurut saya, ini merupakan salah satu cara Orwell untuk menyampaikan ide yang cukup membuat pembacanya betah berlama-lama untuk tidak segera menuntaskan bukunya.
Bukankah ketika berhadapan dengan santapan lezat kita cenderung menahan diri untuk langsung menghabiskannya agar kita bisa menikmati makanan tersebut secara perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sehingga tak ada bagian dari makanan itu yang terlewatkan?
Saya pikir, salah satu alasan mengapa buku dapat dikatakan baik ialah karena kemampuannya untuk menghadirkan nuansa seperti itu.
Cyril Connolly, salah seorang pengulas Burmese Days, di majalah New Statesman tertanggal 6 Juli 1935 menyebutkan bahwa Burmese Days adalah novel yang mengagumkan. Novel ini merupakan sindiran keras bagi orang-orang Anglo-India.
“Si penulis,” kata Connolly, “mencintai Burma sekalipun ia sendiri tetap berusaha untuk menggambarkan sifat buruk orang-orangnya serta kengerian iklim di sana.”
“Saya menyukainya dan merekomendasikannya kepada siapa pun yang menikmati serangkaian kemarahan yang efisien, deskripsi grafis, narasi yang sangat baik, kegembiraan, ironi dan kemarahan,” tulis Connolly.
Ketidakadilan–yang kemudian dibingkai dengan latar kolonialisme dan imperialisme Inggris, menjadi salah satu tema dalam Burmese Days; bersandingan dengan kisah percintaan, persahabatan, dan loyalitas.
Pada saat menuliskan ketidakadilan, Orwell tampak sedang menunjukkan amarahnya terhadap kondisi yang terjadi di tanah koloni milik kerajaan yang mana matahari pun enggan untuk tenggelam di sana.
Sikap itu ia tunjukkan melalui tokoh protagonisnya bernama John Flory: seorang perantau berumur tiga puluh tahun yang berangkat dari Inggris menuju distrik Kyauktada, Burma.
Flory, yang berkawan akrab dengan seorang dokter pribumi bernama Dr. Veraswami menganggap bahwa cengkeraman kerajaan Inggris di Burma tak lain adalah bentuk eksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam meskipun mereka berdalih hendak memajukan bangsa tersebut, menjadikannya lebih beradab.
Inggris sendiri menduduki Burma selama satu seperempat abad, tepatnya mulai dari tahun 1824 sampai 1948. Wilayah tersebut takluk di tangan kerajaan Inggris setelah melalui tiga kali peperangan.
Pada mulanya, pencaplokan daerah Burma dilakukan dengan tujuan untuk menahan dominasi Perancis di Asia Tenggara. Namun, kenyataannya tujuan Inggris menguasai daerah Burma juga untuk mengeruk sumber daya alamnya seperti kayu jati, tembaga, timah dan batu bara.
Orwell menganggap bahwa dominasi kerajaan Inggris atas wilayah Burma sebagai suatu “kebohongan bahwa kita di sini untuk mengangkat saudara-saudara kulit hitam kita yang malang daripada merampok mereka.”
Orwell menulis Burmese Days setelah melewati beberapa tahun yang melelahkan di Burma sebagai Polisi Kerajaan Inggris. Selama lima tahun itu ia memperoleh pengalaman yang–seturut penuturan pribadinya–bertentangan dengan hati nurani.
“Tahun-tahun di Burma telah memberikan saya banyak pengertian akan sifat dasar imperialisme dan memperkuat kebencian alamiah saya terhadap orang-orang yang berkuasa. Pada titik tertentu, hal itu juga menyadarkan saya akan keberadaan kelas pekerja,” tulisnya.
Sebagai agen kerajaan yang ditugaskan di kota Katha dan Moulmein, tentu saja Orwell sering menemui hal-hal yang menyedihkan terkait kondisi penduduk di Burma sehingga menyebabkannya merasa bersalah.
Pernah suatu ketika Orwell dihantui oleh wajah-wajah tahanan di galangan kapal dan di sel-sel penjara. Begitu pula dengan bawahan yang ia rundung serta petani-petani tua, para pelayan dan kuli yang pernah ia pukul dengan tongkatnya.
Dalam esainya Shooting an Elephant, Orwell menganggap bahwa imperialisme Inggris adalah suatu hal yang keji. “Dengan menjalani pekerjaan seperti itu Anda dapat menyaksikan kekejian Imperium Britania dari dekat dan secara langsung,” katanya.
Ia menyaksikan sendiri para tahanan malang yang berkerumunan dalam kurungan pengap, wajah-wajah muram para narapidana dengan masa hukuman yang panjang serta pantat-pantat penuh luka dari mereka yang dicambuki dengan bambu.
“Semua itu membuat saya merasa amat berdosa,” ungkap Orwell. Keseluruhan pengalaman itu ia kumpulkan dan kemudian menjadi inspirasi utamanya dalam menulis Burmese Days. Entah mengapa membaca Burmese Days mengingatkan saya kepada novel Max Havelaar karangan Multatuli.
Buku tersebut menceritakan pengalaman Max Havelaar, seorang pejabat idealis kolonial Belanda yang bekerja di Jawa. Saya pikir, Havelaar sama seperti Flory. Mereka berdua adalah alter ego penulisnya masing-masing.
Dalam buku itu diceritakan bahwa Havelaar menemukan penduduk Jawa yang jatuh kelaparan akibat kebijakan cultuurstelsel pemerintah Belanda. Di sana ia melihat ibu-ibu menjual anaknya demi mendapatkan sesuap nasi; ibu-ibu memakan anak-anaknya sendiri.
Max Havelaar yang merasa bersalah kemudian memberontak dan melawan sistem tanam paksa yang mengerikan itu. Sama halnya dengan Flory yang mengkritik penerapan sistem kolonial Inggris di Burma.
Memang, Burmese Days bukan novel yang mengguncang layaknya Max Havelaar sehingga mampu menginspirasi gerakan liberal di Belanda. Bukan pula seperti Uncle Tom’s Cabin karya Harriet Beecher Stowe yang memberikan amunisi pada gerakan abolisionis di Amerika Serikat.
Tapi, setidaknya kita mengetahui satu hal: bahwa melalui novel tersebut, sepertinya Orwell hendak menebus dosa-dosa kolonialnya.
Judul: Burmese Days
Penulis: George Orwell
Penerjemah: Endah Raharjo
Penerbit: Diva Press
Jumlah halaman: x + 482 halaman
Oleh: Inan
(Dukung kami untuk terus menyajikan tulisan berkualitas dengan berdonasi di sini.)